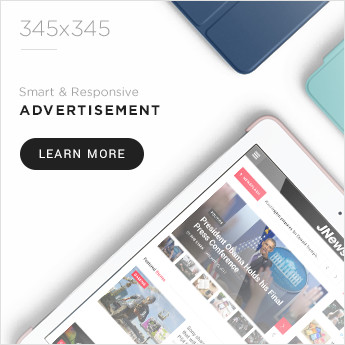Ilustrasi gambar (dok Merpos).
Pada suatu waktu dalam sebuah cerita, di kampung kecil bagian selatan Bumi ini, “Segi Lima”, letaknya yang jauh dari gemerlap kota, tak tercatat dalam peta dunia, di mana suara burung bersahutan setiap pagi dan angin berbisik lembut di antara pohon-pohon kelapa, hiduplah seorang gadis bernama Rapuhncel. Hidupnya sederhana, seperti sungai kecil yang mengalir tanpa riak besar. Namun, siapa sangka di balik kesederhanaan itu, tersimpan luka yang lebih dalam dari samudra, lebih perih dari duri yang menghujam hati.
Ia tinggal di sebuah rumah tua bersama ayahnya, Made, seorang lelaki yang lebih banyak menghabiskan waktunya dengan botol tuak daripada dengan keluarganya. Ibunya sudah lama tak lagi berada dalam dunia yang sama jiwanya hilang entah ke mana, terperangkap dalam kesunyian yang tak bisa dijangkau siapa pun (depresi). Baca juga: Cara Abunawas Deteksi Pencuri Semangka 1,5 Kilogram
Malam-malam di rumah itu tak pernah membawa ketenangan bagi Rapuhncel. Ketika semua orang di kampung terlelap dalam mimpi, di kamarnya yang gelap, ia harus menanggung sesuatu yang lebih kejam dari mimpi buruk.
Malam itu dingin. Angin bertiup pelan, menggerakkan tirai lusuh di jendela kamar Rapuhncel. Ia memeluk lututnya erat-erat, berharap malam segera berlalu. Namun, suara langkah itu datang lagi, berat, menyeret ketakutan yang lebih mengerikan daripada gelapnya malam.
Pintu berderit terbuka. Rapuhncel tak berani menatap. Ia hanya bisa menggigit bibirnya, menahan air mata yang sudah lama ia biasakan untuk tidak jatuh.
“Jangan takut, ini rahasia kita berdua,” bisik suara yang seharusnya menjadi pelindungnya.
Namun, bagaimana bisa seseorang yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru menjadi badai yang menghancurkan? Bagaimana mungkin tangan yang seharusnya membelai dengan kasih justru menjadi belenggu yang merenggut segalanya?
Malam-malam itu berulang, seperti hukuman yang tak pernah berakhir. Rapuhncel belajar membungkam kesakitannya, belajar menyembunyikan tangisnya. Ia tahu, di rumah itu, tak ada yang bisa menyelamatkannya.
Bulan demi bulan berlalu. Tubuh Rapuhncel mulai berubah. Ia merasakan ada sesuatu dalam dirinya yang berkembang, sesuatu yang tak ia pahami. Dengan hati yang gemetar, ia memberanikan diri bertanya kepada Made.
“Ayah… tubuhku berubah, aku tidak lagi datang bulan.”
Made terdiam. Wajahnya tegang, bukan karena rasa bersalah, tetapi karena ketakutan. Ia sadar, dosa yang ia sembunyikan dalam gelap akan segera tersingkap oleh cahaya siang.
Dengan tergesa, ia mengambil kendi berisi cairan bening dan menyodorkannya kepada Rapuhncel.
“Minumlah ini, Nak. Semua yang seharusnya tidak ada, harus dihilangkan,” katanya, suaranya berat, nyaris seperti ancaman.
Rapuhncel ragu. Tangannya gemetar saat menerima kendi itu. Ia memandang cairan di dalamnya, bening seperti air mata yang tak pernah ia izinkan jatuh. Namun, ia telah terbiasa patuh. Tanpa bertanya lebih jauh, ia meneguknya.
Tapi tak ada yang berubah. Hanya tubuhnya yang semakin lemah, semakin rapuh. Wajahnya semakin pucat, langkahnya semakin gontai. Ia merasa seolah-olah jiwanya telah diambil bersamaan dengan segala kepercayaannya pada dunia.
Suatu pagi hingga sore, Air Mata Rapuhncel pecah setelah ia muntah – muntah. Sedang seorang kerabat ibunya juga datang berkunjung di rumahnya. Wanita itu memperhatikan Rapuhncel dengan cermat, melihat matanya yang sayu, kulitnya yang pucat, dan gerak-geriknya yang penuh ketakutan.
“Anakku, mengapa wajahmu seperti bulan yang tertutup awan?”
Saat itu, dinding yang selama ini Rapuhncel bangun di dalam hatinya runtuh. Ia tak bisa lagi menahan semuanya sendirian. Dengan suara lirih, ia menceritakan apa yang selama ini ia pendam, tentang malam-malam yang panjang, tentang ketakutan yang terus menghantuinya.
Rapuhncel kemudian diperiksa oleh seorang perempuan tabib di kampung bernama Hj. Jum. Dari sini mulanya diketahui usia Kehamilannya.
Malam itu, kabar itu menyebar ke seluruh kampung. Orang-orang berkumpul di balai desa, suara kuda yang ditunggangi sekelompok pemuda lalu – lalang dalam reaksi, wajah mereka penuh kemarahan dan ketidakpercayaan.
Di rumah kepala kampung, A Ical, tempat Made semula diamankan, para tetua duduk dalam diam, sementara kepala kampung memandang Made dengan mata yang penuh dengan penilaian.
“Wahai Made,” suara seorang tetua akhirnya terdengar, berat dan penuh kemarahan yang tertahan. “Engkau telah melakukan dosa yang lebih hina dari seorang pencuri! Kau bukan hanya merampas kehormatan putrimu, tetapi juga merenggut seluruh cahaya dalam hidupnya!”
Tak ada lagi tempat bersembunyi bagi Made. Ia bukan lagi seorang ayah, bukan lagi seorang kepala keluarga. Ia hanyalah seorang pendosa yang akan mempertanggungjawabkan segalanya di hadapan manusia dan Tuhan.
Sementara itu, di rumah yang dulu menjadi tempat penderitaannya, Rapuhncel menatap langit yang kini terasa lebih lapang. Tangannya perlahan mengusap perutnya yang mulai membesar, tempat di mana nyawa baru sedang tumbuh.
Air matanya mengalir, bukan karena ketakutan, tetapi karena kelegaan. Ia tahu, malam-malamnya mungkin masih panjang, luka jiwanya mungkin tak akan sembuh dalam sekejap, tetapi setidaknya, hari ini langit telah bersuara untuknya.
Dalam hidup, kejahatan mungkin bisa bersembunyi di balik dinding-dinding rumah, tetapi ia tak akan pernah benar-benar tersembunyi dari cahaya kebenaran. Kezaliman mungkin bisa bertahan dalam gelap, tetapi ketika saatnya tiba, ia akan terungkap dengan sendirinya.
“Kebenaran itu mungkin tertunda, tapi ia tidak akan pernah terbunuh. Dan kebatilan itu mungkin berjaya, tapi ia tak akan pernah kekal,” kata pemimpin kampung.
Sejak terungkap kebenarannya, Made langsung digiring ke penjara menyusul penjemputan paksa oleh Prajurit – Mobile dari kerajaan negeri bagian Utara membidangi Hukum – Penegakan Hukum, para sektor di kerajaan itu mengumpulkan bukti. Made mengakui perbuatannya.
Prajurit Istana mengumumkan peristiwa yang terjadi, dunia dan seisinya sontak tercengang, tercatat dalam sejarah sejak hari itu, keadilan akhirnya datang, Made di penjara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.